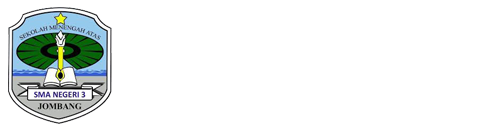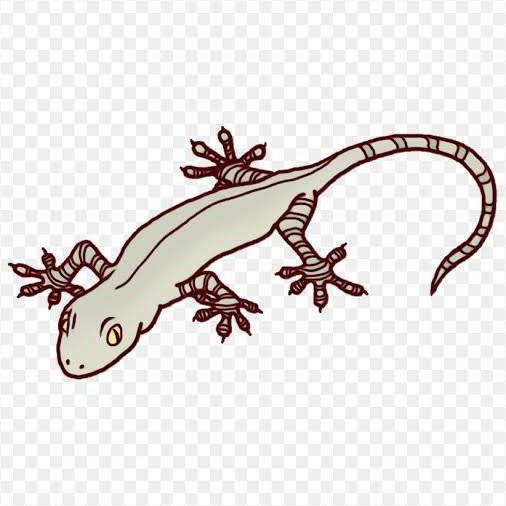
Sebenarnya aku ingin cepat-cepat bercerai dengan istriku karena ia tak bisa memberikan apa yang kuharapkan. Untuk itu, ternyata persoalannya tak semudah melepas pakaian dari badan atau melepas sepatu dari kaki.
Dalam masa perkawinan yang masih terhitung dini ini, bagaimana hal itu bisa kulakukan? Bagaimana orang tua kami yang telah amat menyetujui dan merestui perkawinan kami? Bagaimana saudara-saudara kami yang sebelumnya telah mengetahui keakraban kami yang seakan sulit terpisahkan? Bagaimana pula halnya dengan tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, dan KUA yang beberapa hari kemarin telah meresmikan perkawinan kami?
Mungkin karena itulah, aku tak segera menceraikannya. Aku mesti memerlukan tempo, entah tiga atau dua bulan. Pada hematku, lebih cepat lebih baik. Dalam masa “persiapan” perceraian itu terpaksalah aku bersandiwara di hadapan orang tua dan mertuaku.
Hari-hari ini peraduan kami bagai kuburan saja suasananya, lebih-lebih pada malam hari. Dinginnya malam yang senantiasa melayapi kami tak mampu membangkitkan hasratku untuk menjalankan fungsi sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri. Meskipun aku tidur seranjang dengan istriku, hasrat kelelakianku sedikit pun tidak keder. Sering ia kelihatan gelisah menanti belaian dan jamahanku, namun sedikit pun aku tak hendak menyentuhnya. Mulutku saja malas dan terasa kelu untuk berbicara dengannya, apalagi menyentuhnya. Sengaja kulakukan ini agar cintaku secepatnya longsor dan pada akhirnya beralih pada kebencian. Dengan demikian, proses perceraian kami akan lebih cepat terjadi karena di antara kami sudah tidak rasa cinta lagi secuil pun.
Memang aku telah terikat dengannya, tetapi secara batin ikatan itu sebenarnya tidak ada. Aku menganggap perkawinan itu tak pernah terjadi. Diriku tetap bujang saja layaknya. Lihat saja, apa yang aku lakukan terhadap istriku? Tidak ada yang dapat diidentifikasikan bahwa tindakanku mencerminkan tingkah seorang suami! Ini berarti antara aku dan istriku tidak ada benang-benang halus yang menyatukan kami.
Untuk kesekian kalinya, aku membiarkan malam yang dingin itu berlalu dengan tenangnya. Kubiarkan dinginnya malam itu menjamahi dan menji1ati tubuh istriku. Kubiarkan dinginnya malam itu membelai-belai rambutnya, mengecup-ngecup keningnya, kupingnya, pipinya, hidungnya, dan bibirnya. Dan kubiarkan dinginnya malam itu ber- karonsih dengannya. Sprei yang selama ini masih tetap putih itu kubiarkan ludes dijadikan ajang persetubuhannya dengan dinginnya malam.
Waktu terus bergulir melalui terbit dan tenggelamnya matahari. Dalam pada itu, kebersamaan kami kian membosankan saja dan keinginanku untuk menceraikannya semakin menggebu. Di mataku, istriku semakin memuakkan dan menjijikkan. Kecantikan dan kemolekan tubuhnya menjadi tampak suram dan suram tertutup oleh noda besar yang tak mudah terhapuskan. Ia ternyata perempuan kotor, perempuan lacur yang tak pantas hidup berdampingan denganku. Siapa dia sebenarnya, terlihat dengan jelas.
“Aku laki-laki punya harga diri, Yanti! Bagiku pantang hidup berdampingan dengan perempuan seperti kamu,” bisikku padanya dalam kenyenyakan tidurnya. “Maafkan aku, Yanti, terpaksa aku harus menceraikanmu!”
Ia tak terusik oleh bisikanku. Kulihat ia tetap tidur pulas. Mukanya sedikit pucat (pucat?). Dan, oh, dasternya tersingkap sebatas paha! Tapi, ah, ia perempuan kotor!
Kualihkan pandanganku menerawang langit-langit kamar. Kucoba untuk tidur tapi tak bisa. Lamat-lamat terdengar suara langkah kaki sekelompok orang di jalan depan rumah. Mereka saling berbicara dan cekikikan – entah karena apa. Mungkin mereka baru saja pulang dari jagong bayi di rumah Kang Mitra, istrinya melahirkan anak ketiganya kemarin. Suara langkah kaki mereka pelahan-lahan lenyap ditelan kesunyian malam. Dan dalam kesunyian itu kutemukan lagi diriku sepembaringan dengan istriku, dingin dan membeku.
Entah mengapa, langit-langit itu jadi penuh gambar. Kujumpai di sana orang tua kami, sahabat kami, tetangga kami, dan saudara kami. Terngiang di telingaku tanya dan komentar mereka tentang perceraian kami nanti. Pikiranku terusik juga. Aku pun getol mempersiapkan kata-kata yang tepat sebagai jawaban atas pertanyaan dan komentar mereka. Tapi apa peduli mereka? Toh, mereka orang ketiga dalam konteks perkawinan kami. Perceraian kami adalah urusanku dengan Yanti, istriku. Tidakkah lebih baik kubiarkan saja mereka berkoar-koar mengatakan ini dan itu? Aku yang memegang hak kuasa cerai atas istriku, mengapa aku mesti mempedulikan mereka? Ah, persetan dengan mereka!
“Uaaahm!”Aku menguap dan menguap. Rupanya rasa kantukku tak dapat kuajak kompromi demi memecahkan persoalan itu. Aku pun tertidurlah!
Bagaimana keluarga kami? Pertanyaan ini terngiang lagi di telingaku. Aku jadi ragu memukulkan palu keputusan cerai ke meja hijau perkawinan kami, padahal palu itu telah erat kugenggam dan telah kuangkat tinggi-tinggi. Pelahan tanganku pun lunglai turun dari ketinggiannya; genggamanku jadi lemah terurai, dan palu itu pun lepaslah dari genggaman. Perceraian itu berarti juga perceraian keluarga kami karena perkawinan kami adalah juga perkawinan keluarga kami. Hubungan keluargaku dengan keluarganya menjadi lebih akrab semenjak kami memasuki jenjang perkawinan. Orang tua kami telah resmi berbesanan. Bagaimana halnya dengan mereka saat kami bercerai nantinya?
Sementara pikiranku dalam kekalutan, mataku tertambat lagi pada istriku yang tertidur nyenyak di sampingku ini. Dasternya semakin jauh tersingkap di atas pahanya yang mulus itu, tapi mataku rupanya enggan lama-lama menatapnya. Pandanganku pun beralih lagi ke langit-langit kamar. Aku menerawang kosong ke arah sana karena aku tidak tahu bagaimana sebaiknya aku berbuat nanti.
Entah mengapa, sesaat setelah itu pandanganku tertambat pada dua ekor cicak di plafon kamar. Mungkin karena pandanganku terhalang oleh cicak-cicak itu? Tak tahulah! Tapi, diam-diam aku memperhatikannya. Ulah kedua ekor cicak itu semakin menarik saja. Binatang yang bagi sebagian orang menjijikkan itu berkejar-kejaran dalam kebirahiannya. Setelah satu peristiwa selanjutnya terjadi, tahulah aku bahwa yang mengejar itu si jantan dan yang dikejar itu si betina.
Aneh memang, tapi begitulah kenyataannya, bahwa peristiwa sumir yang terjadi pada cicak-cicak itu memberikan bahan baru dalam pikiranku. Aku berkaca pada diriku sendiri. Aku mengintrospeksi diriku sendiri. Kususuri sebagian tindakanku yang telah kulakukan. ….
Ucapan istriku tiga bulan yang lalu, saat malam pertama kami, kembaIi terngiang dalam telingaku. Dalam rintihannya ia memohon padaku, “Maafkan aku, Mas, aku ….”
“Cukup!” kuputus kata-katanya karena aku muak mendengar alasannya waktu itu. Kata-kata kasarku meluncur deras menapaki mukanya. Aku tak menyangka bahwa aku ternyata bisa bersikap kasar terhadap perempuan, dan itu justru kulimpahkan kepada istriku.
“Tapi aku bukan perempuan hina yang menjajakan kehormatannya kepada lelaki hidung belang. Jangan kausamakan aku dengan mereka, Mas!” sedunya waktu itu. Ia telah mengatakan semuanya dengan sejujur-jujurnya (dengan sejujur-jujurnya?)
Aku menggeliat karena kepayahan mengutak-atik otakku. Tanpa kusengaja tangan kananku menyentuh buah dadanya. Kontan saja ia terbangun karena terkejut.
“Ada apa, Mas?”
“Hm … hm …!” Aku hanya mendeham saja karena gugup dengan apa yang akan kukatakan.
“Mas?” Ia memandangiku penuh tanda tanya.
“E…, tidak, Yanti!” Aku masih gugup juga, entah kenapa. “Maafkan aku, Yanti, aku telah mengganggu tidurmu!”
“Hah!” dengusnya. Ia tampak jengkel karena sikapku; ia pun membalikkan tubuhnya membelakangiku.
Kokok ayam pertama sayup-sayup mengisi kedinian pagi itu dan menyusup menyelinap ke dalam kamarku, kamar kami, melalui lubang-lubang di atas jendela itu.
Cicak itu telah hilang dari pandanganku. Aku tersadar kembali pada keberadaanku semula.
Suara azan Subuh dari mushola yang tak jauh dari rumah mulai berkumandang. Aku segera beranjak mengambil air wudu, dan bergegas melangkahkan kaki menuju panggilan itu.
Ya Allah, betapa dungunya aku waktu itu! Tanpa kusadari aku senyum-senyum sendiri. Peristiwa itu kurasakan amat lucu kini.
“Ada apa, Mas, kok senyum-senyum sendiri?” tanya istriku.
Aku terhenyak. Ternyata istriku yang duduk membaca koran di sana memperhatikanku.
“Ah, tidak ada apa-apa, kok!” bohongku. Istriku pasti tahu kalau aku sedang berbohong padanya. Itu dapat kulihat dan kupastikan dari model senyumannya. Tapi ia cukup tenggang hati dengan hal-hal semacam itu. Itulah kehidupan kami, aku dan istriku, Yanti. Tak jarang kebohongan semacam ini mewarnai kehidupan rumah tangga kami. Dan….
“Pa, belikan itu!” Si kecil, putri kami yang ketiga, berlari-lari dari luar menghampiriku, ia merengek-rengek minta balon mainan yang dijajakan seseorang di seberang jalan sana. Rengeknya persis rengek ibunya sewaktu meminta ….
Jombang, Mei 1990, p4kjee